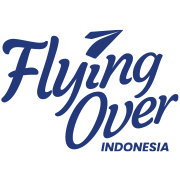Jika umur 40-an adalah fase tua dari masa muda, maka umur 50-an adalah fase muda dari masa tua. Saya ingat kata-kata itu saat mencoba merefleksikan kembali hayat dan karya Toni Pogacnik dalam sejarah sepakbola Indonesia.
Lahir pada 1913, Pogacnik mulai melatih Indonesia pada 1954. Itu tepat saat ia berusia 41 tahun, awal fase usia 40an, dan fase tua dari masa muda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia bukan hanya menancapkan folklore dan mitologi lewat skor 0-0 saat menghadapi Uni Soviet di Olimpiade Melbourne 1956. Dia juga membawa Indonesia masuk empat besar Asian Games 1954, mendapatkan perunggu Asian Games 1958, juga menjuarai Merdeka Games 1962 dengan catatan gemilang tak terkalahkan.
Skandal suap jelang Asian Games 1962 di Jakarta menjadi awal dari keruntuhan era Pogacnik. Itu bukan hanya menghancurkan fondasi tim yang cikal-bakalnya sudah dia siapkan sejak 1954, tapi terutama juga menghancurkan hatinya.
Keruntuhan era Pogacnik menemui kesempurnaannya saat dia mengalami cedera lutut pada 1963. Sebagai pelatih berwatak trainer, yang tak pernah mau duduk anteng melihat pemainnya salah melakukan teknik menendang atau menyundul atau mentekel, cedera itu menyulitkannya untuk turun langsung memberi contoh pada para pemain.
Dia pun pensiun pada 1964. Saat itu dia tepat berusia 51 tahun, awal fase usia 50-an, fase muda dari masa tua.
Pogacnik mengisi fase muda dari masa tuanya itu dengan menjauhi Jakarta --kota yang membawa namanya harum dan pernah pula melukai hatinya. Bersama istri terkasihnya, dia menyepi dari hiruk pikuk sepakbola, pergi ke Bali, membuka sebuah wisma turis di pantai Kuta Bali.
Pada 1971, wartawan Tempo, Yusril Djalinus, mengunjunginya di Bali. Usianya saat itu 58 tahun, menjelang akhir fase usia 50an, menjelang akhir fase muda dari masa tua.
Laporan Yusril berjudul "Dari Bali Berkisah Toni Pogacnik", tayang di majalah Tempo edisi 21 Agustus 1971, dan itulah satu dari sangat sedikit laporan yang bisa digunakan oleh siapa pun yang hendak berterimakasih pada kontribusi Pogacnik dengan cara membaca riwayat hidupnya.
Dalam laporan yang jadi referensi utama bagian ketiga serial tulisan Hikayat Toni Pogacnik itu, Toni mengaku memang agak menjauhi sepakbola. Tapi bukan berarti dia tak lagi nonton sepakbola. Dia masih kadang pergi ke stadion atau lapangan untuk menonton pertandingkan antarklub atau antar-pelajar di Denpasar.
"Tetapi saya selalu menghindari duduk di tempat VIP. Biarlah sekarang ditengah-tengah rakjat," ujarnya ketika itu.
Saat itu, Toni masih berstatus sebagai warga negara Yugoslvia. Sebagaimana yang terjadi dengan Paul Cumming beberapa dekade kemudian, usaha Toni untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tak berjalan dengan mudah.
****
Hampir semua orang yang mengalami dan menjadi pelaku langsung sepakbola di era 1950-an sampai 1960-an menyebut Toni Pogacnik sebagai penubuh sepakbola modern Indonesia. Kolomnis Kadir Jusuf, yang di masanya sangat disegani karena otoritas pengetahuan sepakbolanya, bahkan menyebutnya sebagai "Bapak sepakbola modern Indonesa".
Toni memang bukan pelatih pertama timnas Indonesia, bukan pula ekspatriat pertama yang menukangi timnas Indonesia. Choo Seng Que, biasa dikenal dengan sebutan Uncle Choo, sudah lebih dulu menukangi timnas Indonesia. Kami sudah pernah mengulas kontribusi Uncle Choo dalam esai tersendiri beberapa bulan lalu.
Tapi memang karir kepelatihan Uncle Choo terlalu pendek untuk bisa meletakkan dasar-dasar sepakbola yang bisa membekas panjang. Nah, Toni punya privilege dalam soal waktu ini. Dia melatih selama kurang lebih 10 tahun sehingga punya cukup waktu untuk melakukan apa yang dia cita-citakan terhadap sepakbola Indonesia.
Menapaktilasi karier penuh warna Toni di Indonesia memang tidak mudah. Catatan dan dokumen yang terserak dan banyak di antaranya sudah hilang menyulitkan upaya ini. Tapi dengan keterbatasan bahan, hanya mengandalkan riset pada koran-koran lama, beberapa buku, dan sejumlah wawancara dengan mantan anak asuhnya, bisalah disusun beberapa catatan yang menarik.
Pertama, Toni adalah orang yang paling sadar bahwa timnas yang bagus mustahil muncul dari cara yang instan. Setiap pelatih, apalagi dalam negara yang masih sangat muda, harus mau turun langsung mengajarkan bagaimana caranya teknik bermain bola yang benar. Bahkan kendati berstatus sebagai pelatih timnas sekali pun, dia mau turun langsung mendidik anak-anak kecil dalam menguasai teknik-teknik dasar bermain bola.
Sedihnya, itu seperti menjadi kutukan yang terus berlaku sampai sekarang. Bukan sekali dua kita dengar pelatih asing yang dipercaya menukangi timnas mengeluhkan kualitas teknik dasar pemain nasional. Dari Peter Withe, Ivan Kolev, sampai Alfred Riedl, mereka masih harus menyempatkan diri men-drill para pemain timnas dalam sesi pelatnas.
Kedua, Toni juga yang merancang sistem pembinaan yang berjenjang dan sistematis.
Seperti yang telah diuraikan pada bagian kedua serial tulisan ini, Toni membagi Indonesia menjadi tiga zona dan masing-masing zona dibagi menjadi beberapa rayon, dan di bawah rayon dibagi lagi menjadi beberapa distrik.
Latihan dilakukan di tiap-tiap distrik. Setiap distrik dibentuk satu kesebelasan, dan diadu dengan distrik lain. Dari ketiga kesebelasan distrik, dibentuk kesebelasan rayon. Ketiga kesebelasan rayon diadu untuk membentuk satu kesebelasan zona. Dari tiga kesebelasan zona terbentuklah PSSI-1, PSSI-2, dan PSSI-3.
Dan Toni melakukan safari kepelatihan ke hampir semua distrik. Dia bukan hanya mendidik pemain-pemain muda, tapi membekali calon-calon pelatih dengan metode kepelatihan modern di zaman itu.
Ketiga, Toni orang pertama yang sangat aware merancang sistem permainan yang dirasanya cocok dengan karakter budaya dan manusia Indonesia. Itulah sebabnya dia sangat sering bicara tentang bangsa, tentang watak nasional, juga tentang bagaimana Brasil menciptakan Pele yang baginya adalah pekerjaan sebuah bangsa.
Alih-alih mengeluhkan postur pemain yang pendek, Toni malah mencoba memanfaatkan karakter fisik itu sebagai ciri sekaligus kekuatan Indonesia. Dia yang sejak awal sangat sadar bahwa kekuatan pemain Indonesia adalah pada kelincahan dan start-start pendek.
Sampai sekarang, di setiap performa gemilang timnas Indonesia, hampir selalu dicirikan oleh keberhasilan memaksimalkan kecepatan dan sprint-sprint pendek dengan cara yang sangkil dan mangkus. Peter Withe di Piala Tiger 2004 dan Ivan Kolev di Piala Asia 2007 berhasil membawa timnas tampil enak ditonton karena bisa memaksimalkan sayap-sayap Indonesia yang cepat.
Sampai di sini, perlu untuk menyimak apa yang diuraikan oleh Kadir Jusuf dalam sebuah buku langka berjudul "Sepakbola Indonesia: Sistem Blok, Total Football, Mencetak Gol dan Cattenacio". Buku itu langka mula-mula karena sudah sukar didapat, tapi memang sangat jarang ada buku yang memancangkan ambisi me-review sejarah taktik dunia, lalu dibandingkan dengan evolusi taktik sepakbola Indonesia, guna mendapatkan rumusan ideal apa dan bagaimana taktik yang paling tepat bagi karakter sepakbola Indonesia.
Di buku itu, Kadir Jusuf menyebut bahwa Toni baru sampai mewariskan "catatan lepas tentang bagaimana seharusnya pembinaan sepakbola Indonesia secara makro". Kadir juga menyebut bahwa Toni "belum sempat merumuskan pola permainan apa yang cocok dengan ciri khas itu".
Berdasar penelusuran saya, Toni cukup gemar menggunakan formasi 3-3-1-3 atau dalam bentuknya yang lebih ofensif menjadi 3-3-4. Ini adalah sebentuk adaptasi dari sistem verrou ala Karl Rappan yang dipopulerkan oleh timnas Swiss di dekade 1930-an.
Dengan sistem ini, terutama dalam laga legendaris melawan Uni Soviet di Olimpiade Melbourne 1956, Toni menyusun dua garis pertahanan. Garis pertama diisi oleh Rasyid-Kwee Kiat Sek-Chairuddin Siregar. Di barisan kedua ada LT Tanoto di kiri, Thio Him Tjiang di tengah, dan Phoa Sian Liong di kanan. Tiga barisan penyerang ditempati oleh Aang Witarsa di kanan, Ramang di kiri, dan Danu sebagai center voor atau penyerang tengah.
Irama permainan ditentukan oleh satu orang yang berada di antara barisan penyerang dan dua garis pertahanan. Dalam formasi 3-3-1-3, maka '1' orang yang berdiri sendiri di situ ditempati oleh Ramlan Yatim. Toni menyebutnya sebagai "penyerang pertama" untuk sesuatu yang mungkin sekarang lebih fasih disebut sebagai "penyerang kedua" atau second striker.
Yang khas Toni, demikian penuturan Tanoto, dia membentuk imaginary-line yang bentuknya melengkung melingkupi kotak penalti. Dalam istilah sekarang mungkin sejenis final third, tapi imaginary-line ini secara khusus merujuk zona garis tembak lawan. Imaginary-line ini yang menjadi kunci daya tahan pertahanan Indonesia saat berhasil menghadapi lawan-lawan yang dua kali lipat lebih kuat, seperti saat menghadapi Uni Soviet di leg pertama Olimpiade Melbourne 1956.

****
Apa yang telah dilakukan oleh Toni, terutama dalam menyiapkan fondasi sepakbola, dilanjutkan dengan lebih metodologis oleh Wiel Coerver pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Coerver bukan hanya melatih timnas, tapi secara rutin membuat pelatihan dan penataran pada para pelatih di Indonesia.
Selama melatih di Indonesia, terutama saat mendidik pemain-pemain muda, dia mencoba berbagai eksperimen kepelatihan. Eksperimen-ekperimen itu dicatat dan didokumentasikan dengan rapi dan kemudian dari situlah lahir apa yang dalam jagat sepakbola internasional dikenal sebagai "Metode Wiel Coerver". Metode Coerver ini sangat masyhur dan banyak jadi acuan pembinaan sepakbola di seluruh dunia dan diakui FIFA sebagai salah satu standar.
Toni tak mencapai privilege seperti yang dinikmati Coerver. Dia adalah perintis, sang pemula, sang peletak dasar.
Maka ketika akhirnya dia tak tahan melihat jebloknya prestasi timnas, dia pun kembali menukangi timnas yang dipersiapkan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 1978. Sayang, iswadi Idris, dkk., yang diasuhnya gagal memberi prestasi yang memuaskan. Dia pun terpaksa tahu diri dan memutuskan mundur.
Toni saat itu sudah mulai beraktivitas kembali di Jakarta. Penelusuran kami terhadap beberapa orang yang kenal dengan Toni di Bali, bisa diketahui bahwa saat itu penghasilan Toni dari mengelola losmen Waru Laut di Kuta sudah tak cukup. Tamu hotel makin lama makin sepi. Makanya dia memutuskan kembali ke Jakarta.
Setelah gagal di timnas senior yang dipersiapkan untuk Piala Dunia 1978, Toni kemudian muncul kembali dengan tawaran membuat sebuah pembinaan sepakbola usia muda.
Pada April 1978, dia bicara kepada wartawan untuk membantunya mengembangkan pemain-pemain muda. "Bagaimana memassalkan sepakbola bocah sebagai dasar untuk menopang pembentukan tim-tim nasional yang tangguh," katanya seperti terbaca pada Tempo, edisi 27 Mei 1978.
Sayang sekali, belum sampai mimpi itu tercapai, Toni keburu meninggal pada 21 Mei 1978. Dia terkena serangan jantung.
Dan, tahukah Anda, bahwa Toni meninggal ketika baru saja dia menerima status sebagai warga negara Indonesia. Dia wafat pada 21 Mei, status WNI diterimanya pada 13 Mei. Status itu diterimanya setelah bertahun-tahun menunggu, setelah dia memberi banyak sumbangan mengangkat nama Indonesia ke kancah sepakbola Asia. Nasib serupa hampir sama dengan yang dialami oleh Paul Cumming belakangan.
Dia bukan hanya pergi meninggalkan istri dan seorang anak yang saat itu sudah tinggal di Amerika, tapi juga meninggalkan satu mimpi kecilnya di hari tua: membuat semacam akademi atau sekolah sepakbola. Dan dia sudah bergerak untuk memenuhi mimpi terakhirnya itu.
Ia sudah mendatangi kantor Gelora Senayan yang saat itu baru berganti pimpinan dari R. Sumantri kepada Gatot Suwagio. Kepada mereka, dia utarakan rencdanya untuk membinca sepakbola usia muda. Ia sendiri yang datang untuk meminta bantuan disediakan sebidang tanah di sekitar Senayan untuk keperluan lapangan latihan. Sendirian dia mencari donatur yang mau membantu dan dia mengaku sudah mendapatkan donatur.
Sayang ajal tak pernah mau memberi ampun. Mimpi sederhana dan terakhirnya itu belum sempat terealisasi. Setidaknya, bahkan di hari-hari terakhirnya, dia masih ingin berbuat, masih ingin beraksi demi sepakbola Indonesia, kendati saat itu ia sudah berusia 65 tahun dan jelas sudah memasuki masa tua.
Itulah barangkali yang akan dilakukan oleh setiap orang tua yang tak pernah berhenti berpikir. Bertindak dan berbuat justru jadi kebutuhan menjelang hari akhir.
Sebab masa tua, sebagaimana dikatakan Cicero, "Adalah mahkota kehidupan sekaligus tindakan terakhir yang kami lakukan."
Demikianlah hikayat Antun Pogacnik. Kisah tentang lelaki tua dan sepakbola.
====
*akun Twitter penulis: @zenrs dari @panditfootball
*Foto-foto:
1. Pogacnik saat melatih anak-anak (Pandit Football Indonesia)
2. Taktik Pogacnik dari buku "Sepakbola Indonesia: Sistem Blok, Total Football, Mencetak Gol dan Cattenacio" karya Kadir Jusuf
Baca Juga:
Bagian 1: 'Menciptakan Pele Merupakan Pekerjaan Suatu Bangsa'
Bagian 2: Perunggu Asian Games 1958 dan Folklore 0-0 di Melbourne
Bagian 3: Suap yang Menghancurkan Pogacnik
(roz/a2s)