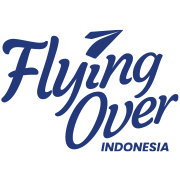Genap hari ini 116 tahun yang lalu —17 September 1898—, lahir seorang laki-laki yang kelak membangun fondasi organisasi sepakbola di negeri ini bernama PSSI. Ironisnya, Soeratin mengisi masa tuanya dalam kesunyian.
*
Sahro masih ingat beberapa bagian dari peristiwa pemakaman itu. Dari jarak 50 meter, dengan peluh di badan dan cangkul di bahu, ia menyaksikan prosesi pemakaman seseorang yang dilihatnya sendiri, pemakaman seorang tokoh penting dalam sejarah sepakbola Indonesia: Ir. Soeratin Sosrosoegondo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sahro mencoba membongkar lapisan-lapisan ingatannya.
Sahro adalah penggali kubur di Pemakaman Sirnaraga. Usianya kini sudah 91 tahun. Tiga perempat masa hidupnya diabdikan sebagai penggali kubur di sana. Sudah ribuan jenazah yang liang lahatnya dia siapkan.
Bagi penggali kubur seperti dia, kematian seseorang adalah rezeki. Kematian datang, maka pekerjaan pun datang. Selalu begitu dan begitu. Orang-orang mati datang dalam kehidupannya seperti angin lalu. Karena itu pemakaman Soeratin tak begitu membekas dalam benaknya, terutama karena Soeratin mati sebagai orang biasa. Dia tak menyaksikan para pembesar, para petinggi, orang-orang gedongan dan terkenal ada yang datang dalam proses pemakaman Soeratin. Semuanya berlangsung dengan datar, jauh dari hiruk pikuk, dan tanpa tembakan salvo penghormatan.
Dari penggalan ingatan Sahro itu, Soeratin meninggal dalam keadaan yang sunyi, jauh dari gempita penghormatan. Hanya segelintir orang yang ikut memakamkan Semua warga biasa saja. Tak lebih dari belasan. Jumlah pastinya Sahro sudah lupa.
Tiga tahun kemudian dia baru sadar siapa orang yang dimakamkan di sana. Kubur yang tertanam di pojok dekat sungai kecil dan bilik sederhana itu, sejak 1962, mulai diperhatikan oleh PSSI. Mereka memutuskan untuk memugarnya dan membuatnya lebih layak sebagai sebentuk penghormatan.
Sejak itu, pada batu nisan kuburan itu, diterakan pahatan bertuliskan kalimat: "Pendiri PSSI".
Kini, di pemakaman Sirnagalih itu, orang mudah mencari tahu di mana kuburan Ir. Soeratin. Makam itu kini menjadi salah satu makam penting di situ. Setiap PSSI merayakan ulang tahunnya, selalu ada yang berziarah ke sana. Di masa lalu, setelah pemugaran itu, bukan sekali dua terjadi timnas Indonesia berziarah dulu ke situ sebelum berangkat ke luar negeri. Kadang, klub lokal Persib Bandung pun berziarah lebih dulu sebelum berangkat mengikuti suatu kejuaraan atau turnamen.
Tapi itu terjadi setelah kuburannya dipugar, setelah PSSI sadar untuk menghargai jasa dan peranannya. Jauh sebelum itu, sejak Soeratin hijrah ke Bandung, tak banyak informasi yang bisa digali dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Memoar tentang Soeratin memang menyisakan banyak episode yang berkabut. Tak banyak sejarawan yang terpikat untuk mendalami seluk beluk hikayatnya. Alhasil Soeratin jadi sebuah mitos yang begitu didewakan, padahal tentu ia juga adalah manusia biasa, yang pernah alpa dan wajar juga jika pernah berbuat salah.
Orang hanya tahu kisah Soerartin di masa kolonialisme Belanda, sebelum kedatangan Jepang. Kisah heroiknya mendirikan PSSI sebagai bagian pergerakan dan perjuangan nasional seakan menjadi folklor (cerita rakyat yg diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan) dalam sejarah sepakbola Indonesia.
Tapi orang lupa, atau bahkan tak pernah tahu cerita Soeratin lainnya. Masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan: konflik antara pengurus Yogyakarta dan Solo, alasannya kenapa hijrah ke Bandung, kehidupannya pascapenjajahan Jepang sampai era kemerdekaan, dan kenapa ia mati tragis dalam kondisi melarat. Semua itu masih teka-teki.
Beruntung Wartawan senior Eddi Elison mengkreasi kisah Soeratin dalam sebuah buku biografi yang baru-baru ini terbit. Ada hal-hal baru yang saya temukan dan bisa digali lebih dalam.
Soeratin pernah angkat senjata melawan Belanda sebagai tentara. Mungkin itulah yang Elison ceritakan berdasarkan reportasenya. Cerita ini berdasarkan penuturan Kol. (purn) H.Herrawan A --eks anak buah Soeratin saat bertugas di Citaman, Nagreg, dari tahun 1946 hingga 1947. Beruntung Herrawan tinggal di Bandung. Saya datangi kediamannya di Jalan Gondang, saya keruk ingatannya hingga hal detail. Sayang, jawabannya masih banyak yang berkabut.
Jejak Soeratin memang menghilang di Bandung sesudah kedatangan Jepang. Tahun 1937 Soeratin meninggalkan Yogyakarta dan pindah ke Bandung dengan alasan yang tak bisa diterka. Ada dugaan dia lelah dengan konflik antarpengurus Solo dan Yogyakarta yang terus bertikai demi ambisi menguasai PSSI. Soeratin lebih condong mendukung Solo. Di Yogyakarta ia merasa tidak diterima mengingat konflik PSSI dan PSIM Yogyakarta yang memang masih hangat-hangatnya. Karena itu ia memutuskan pergi ke Bandung dan menyerahkan kepengurusan harian PSSI kepada Dr. Soeratman Erwin di Solo. [baca About The Game: Sejarah PSSI bagian 3]
Di Bandung, sedikit sekali catatan bagaimana nasib kehidupan Soeratin. Apakah kembali bekerja sebagai teknokrat pada pemerintah kolonial? Atau meneruskan bisnisnya di bidang kontruksi sembari membuka biro jasa arsitek seperti yang dilakukannya di Yogya? Entahlah.
Yang jelas pada 1941, saat Kongres PSSI digelar di Bandung, Soeratin terpilih sebagai Ketua Kehormatan. Jabatan itu agaknya bukan jabatan fungsional, melainkan hanya kedudukan formal yang tak berimbas pada praktik keorganisasian PSSI, semacam posisi kehormatan, tapi tak bisa berbuat apa-apa.
Apapun itu, kita tahu, saat Jepang menduduki negeri ini, PSSI mengalami kevakuman. PSSI menghilang, Soeratin pun seperti lenyap. Kabarnya baru muncul lagi setahun setelah Indonesia merdeka.
Saat itu, pada 1946, Soeratin kembali muncul. Dia terlihat lebih tua. Saat itu dia berada pada usia akhir 40an. Badannya kecil, kurus kerempeng, sedikit bungkuk, tetapi sebagai seorang tentara berpangkat Letnan kolonel kondisi fisik itu tak mempengaruhi kewibawaanya sebagai perwira. Sejak itulah beberapa orang mengetahui bahwa Soeratin yang sempat mendirikan PSSI itu, memang sempat menjadi kepala pabrik senjata di Jawa Barat semasa revolusi.
"Dia di bawah penugasan langsung Markas Besar Tentara di Yogyakarta. Ia bukan bagian dari divisi Siliwangi," kata Herrawan.
"Saya tidak tahu apakah dia pernah kembali ke Yogya dan jadi tentaranya di sana. Tapi sepertinya memang begitu karena penugasannya langsung dari pusat."
Saya merasakan keganjilan dari keterangan itu. Sejak kapan Soeratin jadi tentara? Secara logika, saat Jepang datang, usia Soeratin 44 tahun. Umur itu bukan usia ideal masuk jadi tentara. Lantas, mana mungkin dia dengan cepat promosi jadi Letnan Kolonel? A.H Nasution, yang jadi Komandan Divisi III Siliwangi saja waktu itu berpangkat kolonel.
Tapi mengingat jabatan Soeratin sebagai penanggung jawab persenjataan dan ilmunya sebagai seorang insinyur lulusan Jerman, mungkin faktor itulah yang membuat kariernya di militer cepat melesat. Ini baru sebuah hipotesis.
Di Jawa Barat, menurut Herrawan, ia bertanggung jawab mengelola 8 pabrik senjata dan dinamit yang tersebar dari Sukabumi hingga Garut. Di masa revolusi, sebelum Agresi Militer pertama pada 1947, Soeratin tinggal di sebuah rumah tua dekat pabrik senjata di Citaman, Nagreg.
Di rumah bekas kantor pabrik kopi Belanda itu terdapat 4 kamar. Soeratin dan 2 stafnya mendapat masing-masing satu kamar, sedangkan kamar depan diperuntukkan buat tentara dengan pangkat lebih rendah, salah satunya Herrawan.
Herrawan bercerita, ada memang hasrat untuk bertanya kepada Soeratin. Tapi ia tak berani. Jangankan bertanya soal pribadi, menyapa bagaimana kabar dan sedikit bercakap soal kehidupan sehari-hari pun segan dilakukan Herrawan. Lelaki tua itu selalu terlihat sebagai seorang mistikus pendiam, tak banyak ucap, bicara semau dan seperlunya dia.
Setiap senja mulai membayang di sebelah barat, Hermawan dan rekan-rekannya baru pulang kembali ke rumah. Sebagai seorang tentara yang takut pada atasan, mereka langsung tentu masuk kamar. "Saya cuma tentara kroco-kroco, tentu seganlah berbincang-bincang dengan dia," katanya.
Dari bilik dinding, prajurit-prajurit itu tanpa sengaja menguping apa yang seharusnya tak mereka dengar. Sesekali terdengar obrolan rumah tangga, sesekali juga pertengkaran suami istri.
Denting Piano terkadang terdengar di malam hari, yang memainkannya tak lain dari istri Soeratin itu sendiri. Terkadang mereka berduet, Soeratin menggesek biola dan sang istri mengiringinya dengan permainan Piano.
Siapa sangka sang istri yang dibawa turut ke medan laga itu seorang Belanda, bukan Sri Woelan yang adik Dr Sutomo, yang pernah dinikahinya dulu di masa pendudukan Belanda.
"Seorang Belanda?" tanya saya.
"Ya seorang Belanda," jawab Herrawan dengan mantap.
"Bukan Sri Woelan yang orang Jogja itu? Istri lain Soeratin?"
"Wah Saya ndak tahu itu, yang jelas nyonya Belanda itu adalah istirinya," kata Herrawan.
"Namanya siapa, Pak?"
"Saya ndak tahu, saya lupa, tapi kami selalu panggil dia nyonya saja."
Kendati umurnya sudah tergolong cukup tua sekitar 40an, ia tetap cantik dan anggun. Herrawan mengenang, kulitnya putih, hidungnya mancung dan mulai ada sedikit keriput di wajahnya. Seperti seorang noni dan nyonya Belanda, pakaian sehari-harinya tak lepas dari gaun sederahana yang menjuntai ke bawah. Sesekali juga terlihat memakai kebaya layaknya orang sunda. Warna putih tampaknya adalah warna favorit sang nyonya, tercermin dari warna pakaian yang selalu melekat di tubuhnya.
Dapat dipastikan Soeratin mengungsi ke Nagreg pasca kejadian Bandung Lautan Api di awal tahun 1946.
Ada hal yang menarik. Saat kaum Republikein melawan pendudukan Belanda, Soeratin malah menampung seorang Belanda. Di masa itu di Bandung, bebasnya internir Belanda dan Indo-Belanda yang sempat ditahan dalam kamp interniran bikinan Jepang (kamp ada di Cimahi, ada juga di Cikudapateuh, kawasan dekat rel kereta api, tak jauh dari Pasar Kosambi sekarang).
"Mereka itu antek-antek NICA. Mereka berharap dapat memulihkan hak-hak istimewanya lagi sebagai penjajah ketika Jepang menyerah. Dendam mereka kepada Jepang ditumpahkan kepada kita! Ya kita sikatlah," kata Herrawan.
Saya tak tahu apakah sang nyonya sempat menderita di kamp-kamp tawanan Jepang, atau mungkin Soeratin menyembunyikannya? Saya juga tak tahu, Soeratin dan sang nyonya menikah tahun berapa, apakah saat Soeratin datang ke Bandung tahun 1937, sebelum kedatangan Jepang atau sesudah Indonesia merdeka?
Pastinya, saat hidup di antara para pejuang republikein, sang nyonya tidak menunjukan gelagat aneh-aneh seperti mata-mata. Dia mencintai Indonesia seperti mencintai Soeratin suaminya. Kepada para pejuang dia ramah melempar senyum dan sapa. Pandai berbahasa Indonesia dan terlihat lumayan gemar memakai kebaya. Herrawan mengenang, kombinasi faktor-faktor itulah yang membuat para pejuang saat itu malu untuk membencinya.
Dalam buku Biografi "Soeratin", Eddi Elison menyebut nama Sang Nyonya adalah Johana. Sejatinya, sampai sekarang saya tak menemui data otentik mengenai sang nyonya ini. Saya berjanji akan mencoba mencarinya lagi.
====
* Bagian pertama dari 3 tulisan. Ditulis berdasarkan riset pustaka dan wawancara dengan sejumlah narasumber. Akun twitter penulis: @aqfiazfan
** Hak publikasi tulisan milik Pandit Football Indonesia (@panditfootball)
(a2s/roz)