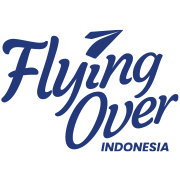Sepakbola adalah model dari masyarakat individualistik. Kalimat itu diucapkan Antonio Gramsci, pendiri Partai Komunis Italia, sekaligus pemikir Marxis yang masyhur dengan konsepnya mengenai hegemoni.
Bagi Gramsi, sepakbola merupakan permainan yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana inisiatif, bakat, kemampuan dan hierarki berkembang di dalam kerangka hukum. Ada gerak, ada kontak fisik, ada benturan, ada juga keindahan dan kejutan – tapi semuanya tak bisa keluar dari aturan main yang diwakilkan kepada wasit.
Gramsci seakan hendak mengatakan bahwa model masyarakat industri, yang menjunjung tinggi spesialisasi, juga terlihat dalam sepakbola. Tidak ada seorang generalis dalam industri. Masing-masing pekerja harus menguasai satu spesialisasi (sebagaimana kiper, bek, gelandang dan penyerang punya keahlian dasar dan tugas masing-masing) dan di bidang itulah dia masuk ke dalam rantai kerja yang memutar roda industri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gramsci tak sempat menyaksikan bagaimana Gustav Sebes meletakkan dasar bagi apa yang kelak disebut sebagai total football melalui taktik sepakbola yang menempatkan setiap pemain dalam posisi yang setara dan bisa memainkan berbagai peran dengan sama baiknya. Dengan formasi dasar 4-2-4, Sebes menyusun taktik yang memaksa sekaligus mengizinkan semua pemain bisa bermain di berbagai area, bisa berperan dalam banyak posisi, dan sama-sama punya tanggungjawab yang sama dalam menyerang maupun bertahan. Sama rata, sama rasa.
Sebagai orang yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Olahraga Hongaria, yang saat itu dikuasai oleh rezim Partai Komunis, Sebes mencoba menerjemahkan gagasan sosialisme ke dalam taktik sepakbola. Terjemahan bebas ala Sebes atas ideologi sosialisme inilah yang melahirkan Magical Magyars, julukan bagi timnas Hongaria di dekade 1950-an, salah satu kesebelasan terhebat yang pernah memainkan sepakbola.
Apa yang dilakukan Sebes terbukti berhasil mengubah taktik sepakbola secara radikal. Keberhasilan Hungaria mengalahkan Inggris di Wembley pada 1953 dengan skor telak 6-3 membuat dunia terbelalak. Taktik sepakbola kemudian pelan tapi pasti mulai berubah dan beradaptasi. Disempurnakan oleh Bella Guttman, terjemahan bebas Sebes terhadap sosialisme ke dalam taktik sepakbola berkembang sedemikian rupa dan sejak itulah taktik sepakbola – meminjam kalimatnya Jonathan Wilson – “tidak pernah sama seperti sebelumnya” (Inventing the Pyramid, hal. 100).
Kaum Komunis Bermain Bola
Gustav Sebes menjadi figur terdepan dalam upaya memperlihatkan kepada dunia bagaimana sosialisme dipraktikkan dalam sepakbola – sebagaimana Maxim Gorky mencoba mempraktikkanya ke dalam prosa, Brodksy dalam seni rupa, Georg Lucasc dalam kritik sastra, hingga Dmitri Shostakovich dalam musik dan opera.
Upaya Sebes ini jelas suatu upaya yang pelik dan mau tak mau penuh improvisasi karena watak sepakbola sendiri yang kompleks dan begitu dinamis. Satu yang pasti: upaya Sebes ini Juga lebih sulit dari sekadar menggunakan sepakbola sebagai alat politik.
Di Indonesia, tidak ada sosok seperti Sebes. Tapi bukan berarti tidak ada upaya mengaitkan sepakbola dengan politik. Seperti sudah berkali-kali diutarakan dalam berbagai artikel yang dirilis oleh kami dari Pandit Football Indonesia, sejarah sepakbola di Indonesia mustahil dibaca tanpa menjelaskan politik sebagai konteksnya.
Siapa pun yang mencoba membaca dan mempelajari sejarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mustahil tidak menemukan penjelasan mengenai konteks politik di Hindia Belanda masa itu. PSSI memang lahir, bahkan walau pun sekarang sudah terdengar klise, di tengah latar kolonialisme dan anti-kolonialisme yang sedang berkontestasi.
Di level pengelolaan sepakbola, pertarungan antara kolonialisme dan anti-kolonialisme bisa diendus dengan mudah lewat berbagai insiden dan kejadian: dari mulai persaingan antara PSSI dengan NIVB (federasi sepakbola Hindia Belanda) hingga sengketa antar aPSSI dengan NIVU (federasi sepakbola Hindia Belanda yang diakui FIFA) dalam soal pengiriman kesebelasan Hindia Belanda ke Piala Dunia 1938.
Salah dua orang tokoh nasionalis yang lumayan intens berinteraksi dengan dunia sepakbola adalah MH Thamrin atau Otto Iskandar Dinata. Sudah menjadi cerita yang banyak diketahui orang bagaimana keduanya menggunakan sepakbola untuk menginjeksi kebanggan terhadap identitas nasional melalui Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ) dan Persib Bandung.
MH Thamrin dan Otto bisa digolongkan ke dalam kelompok nasionalis moderat yang memilih bekerjasama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keduanya sama-sama menjadi anggota Volksraad. PSSI, sampai batas tertentu, juga sebenarnya cenderung moderat dan tidak pernah secara terbuka memainkan peranan sebagai organisasi pembangkang yang berhaluan non-kooperasi. Itulah kenapa PSSI masih bisa mendapatkan izin untuk menggelar berbagai kompetisi tahunan – sesuatu yang tak mungkin terjadi jika mereka mengambil haluan non-ko.
Inilah yang membuat catatan sejarah sepakbola Indonesia tidak lengkap. Seluruh cerita yang umum diketahui tentang sepakbola sebagai alat perjuangan sesungguhnya dimungkinkan dalam kerangka politik kooperasi. Pertanyaannya: bagaimana dengan sepakbola yang dimainkan oleh kelompok-kelompok berhaluan radikal yang menolak berkompromi dengan kebijakan politik kolonial?
Sedikit jawaban yang bisa diberikan untuk pertanyaan ini. Tapi bukannya tidak ada.
Dalam buku The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents yang disusun oleh Harry J. Benda dan Ruth Mc Vey (Equinox Publishing: 2009), saya menemukan sepotong cerita menarik perihal bagaimana sepakbola digunakan oleh orang-orang komunis (hal 147-164).
Di Pariaman, berdiri sebuah kesebelasan bernama LONA yang salah satu pendirinya adalah pemuda bernama Hamzah. Kesebelasan ini bermarkas di Pasar Pariaman. Menurut Benda dan Mc Vey, LONA ini ternyata kesebelasan yang kemudian bertransformasi ke dalam sel Partai Komunis Indonesia (PKI). Dari yang awalnya adalah kesebelasan, LONA lantas berkembang menjadi salah satu organisasi perlawanan yang terkait dengan PKI yaitu Barisan Merah.
LONA, kemudian Barisan Merah, merupakan satu dari sekian banyak organisasi bawah tanah yang berhaluan radikal di wilayah Sumatera Barat. Bersama serikat-serikat petani dengan berbagai nama, juga Sarikat Djongos, Sarikat Itam, dll., Barisan Merah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari radikalisasi kaum komunis di Sumatera Barat. Puncaknya adalah perlawanan bersenjata pada Januari 1927 di Silungkang – gerakan yang tak bisa dipisahkan dari rantai komando PKI di Jawa yang juga melakukan perlawanan bersenjata yang sama di beberapa tempat.
Saya belum menemukan apa kepanjangan dari LONA. Nama ini agak dekat dengan nama kesebelasan di Bandung yang pernah diperkuat Soetan Sjahrir selama bersekolah di HBS. LUNA yang diperkuat Sjahrir ini kepanjangan dari Laat U Niet Overwinnen. Berbeda dengan LONA di Pariaman, kesebelasan dari Bandung ini jelas bukan organisasi ilegal yang bergerak di bawah tanah. LUNA aktif mengikuti kompetisi di Bandung.
Perlawanan bersenjata yang dilakukan kaum Komunis di Sumatera Barat itu juga terjadi di Banten. Radikalisasi di wilayah Banten juga disokong oleh keberadaan berbagai organisasi bawah tanah yang berafiliasi dengan PKI.
Perkembangan gerakan komunis di Banten juga mengalami hambatan karena pemerintah kolonial memang sangat mencurigai aktivitas orang-orang komunis. Rapat-rapat terbuka sudah pasti dilarang.
Seperti diuraikan oleh Michael Charles Williams dalam buku Communism, Religion, and Revolt in Banten (hal. 168), para aktivis komunis itu melakukan rapat-rapat tertutup, kadang kala menumpang berbagai acara seperti selametan atau acara-acara hajatan. Di Serang, kadang mereka bertemu dan melakukan rapat sembunyi-sembunyi di bioskop dengan bepura-pura nonton film.
Di kesempatan lain, masih dari uraian Michael Charles Williams, pertandingan-pertandingan sepakbola di kampung-kampung juga digunakan sebagai lokasi rapat. Kadang malam hari mereka duduk-duduk di tengah lapangan yang gelap gulita.
Main Bola di Tanah Buangan
Setelah perlawanan bersenjata yang diputuskan oleh para pemimpin PKI itu meletus, dengan cepat PKI disikat (nyaris) habis oleh pemerintah kolonial. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam PKI dibuang ke Digul, sebuah tempat terpencil di belantara Papua.
Tak banyak yang dilakukan di Digul. Aktivitas dibatasi oleh alam yang masih liar, fasilitas juga amat terbatas. Selain bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri, para Digulis (sebutan untuk para tahanan politik yang dibuang ke Digul) ini juga menghabiskan waktu dengan – apa lagi kalau bukan – bermain sepakbola.
Untuk mewadahi hobi bermain sepakbola, orang-orang kiri ini membuat perkumpulan bernama Kunst, Sport en Voetbal Vereeniging Digoel (Perhimpunan Seni, Olahraga dan Sepakbola Digul) yang dipimpin oleh Wiranta, penulis buku menarik berjudul Boeron dari Digoel. Wiranta adalah orang Sunda yang di kemudian hari menjadi inspirasi bagi Utuy Tatang Sontani, salah seorang prosais unggul pasca revolusi, yang kemudian juga memilih ideologi politik kiri dengan bergabung dengan Lekra.
Saat Bung Hatta dan Sjahrir juga dibuang ke Digul (dibuang dengan kasus yang berbeda, bukan kasus perlawanan bersenjata PKI 1926/2927), mereka pun ikut gabung perhimpunan ini. Hatta disebut senang bermain sebagai bek kanan dan Sjahrir menjadi sayap kiri.
Suasana intimidatif di tanah buangan ini memang memaksa para Digulis untuk terus bergerak, beraktivitas dan melakukan berbagai hal. Tanpa itu, mereka dengan mudah dilamun pesimisme, depresi dan merosotnya kejiwaan.
Ribut-ribut jadi hal lumrah dalam suasana penuh tekanan macam itu. Kadang dipicu oleh hal sepele, kadang dipicu oleh hal serius seperti bagaimana menyikapi tawaran pemerintah kolonial untuk berkompromi. Siapa yang mau bekerjasama, maka akan mendapatkan fasilitas tambahan selama di Digul. Mereka yang menolak berkompromi biasanya adalah tokoh-tokoh penting PKI, seperti Sardjono, Budisutjitro, Ali Archam hingga Mas Marco Kartodikromo. Mereka yang keukeuh menolak bekerjasama kemudian diasingkan ke tempat yang lebih terpencil di Tanah Tinggi.
Salah seorang Digulis non-PKI, Mohammad Bondan, tiba di tanah pengasingan Digul saat perseteruan itu sudah mulai mereda. Tapi jejaknya masih terlihat oleh Bondan. Seperti terbaca dalam buku Spanning a Revolution: (hal. 148) yang ditulis oleh Melly Bondan, istri Bondan, perseteruan itu bahkan sampai membuat dua kelompok ini bermain sepakbola di lapangan yang berbeda.
Sepakbola di Masa Perang dan Damai
Apa yang membuat elit-elit pergerakan macam MH Thamrin atau Otto Iskandar Dinata maupun para aktivis bawah tanah macam Hamzah di Pariaman merasa perlu untuk menggunakan sepakbola sebagai alat perjuangan politik?
Mungkin klise, tapi memang sukar dibantah: sepakbola adalah olahraga yang mudah dimainkan. Cukup sebidang tanah kosong dan sebuah bola (itu pun bisa buntalan kain, kertas yang digulung atau jeruk bali) maka sepakbola bisa langsung dimainkan. Jumlah orang pun bisa seadanya. Tak harus sebelas lawan sebelas.
Inilah yang membuat sepakbola amat mudah menjalar di tanah Hindia Belanda, juga di negeri-negeri jajahan lain di seantero muka bumi. Dari yang mulanya permainan orang-orang kulit putih, sepakbola dengan cepat memikat penduduk bumiputera. Bond-bond sepakbola dengan mudah tumbuh, mulai dari kota-kota besar macam Surabaya, Jakarta, Bandung atau Makasar, hingga kota-kota kecil seperti Pariaman, Serang hingga Digul yang terpencil. Koleksi KITLV maupun Troopen Museum banyak menyimpan dokumentasi foto yang memperlihatkan antusiasme penduduk bumiputera terhadap permainan sepakbola ini.
Simaklah bagaimana Sukarno menjelaskan kegilaan penduduk Indonesia terhadap pemain ini, seperti terbaca dalam majalah Olahraga, 1 April 1953: “Bola disukai oleh anak di kota dan di desa, dan mulai ketjil kita semua sudah menjadi pemain bola. Di sekolah, kita mulai main sepakbola setjara teratur, meskipun belum sungguh-sungguh!”
Sepakbola akhirnya menjadi sebuah peristiwa sosial karena mampu melibatkan begitu banyak orang, tak hanya sebelas lawan sebelas. Antusiasme penonton terhadap pemain ini memungkinkan pertandingan-pertandingan sepakbola mudah digunakan untuk alat propaganda. (pada tulisan selanjutnya saya akan menguraikan bagaimana sepakbola digunakan untuk membentuk mentalitas revolusioner di era 1950-1960an).
Mestikah diherankan jika Tan Malaka, salah seorang tokoh penting komunis Asia sebelum Perang Dunia II, pendiri beberapa partai komunis di Asia Tenggara, juga menggunakan sepakbola sebagai sarana membangun dan merawat semangat di kalangan para pemuda progresif.
Saat membangun sel-sel perlawanan bawah tanah di Banten Selatan di masa pendudukan Jepang, Tan Malaka bukan hanya membentuk kelompok sandiwara, tapi juga membuat kesebelasan sepakbola bernama Pantai Selatan. Mereka rutin berlatih dan kadang kala bertanding dengan kesebelasan di Rangkasbitung.
Dalam situasi yang penuh keterbatasan, tekanan dan intimidasi, tak cukup membangun ideologi melalui diskusi-diskusi tanpa henti. Kekuatan pikiran mesti diimbangi oleh daya tahan fisik yang memadai. Jika pikiran dibutuhkan untuk terus menerus melakukan analisis situasi ekonomi politik, daya tahan fisik dibutuhkan karena situasi yang tak menentu sangat mungkin berubah dengan cepat sehingga perlawanan boleh jadi mesti dilakukan secara fisik, dengan mengungsi sambil bergerilya, dengan berlari sambil melakukan perlawanan bawah tanah.
Inilah yang juga terlihat dan terjadi pada para aktivis PKI di tanah Jawa selama era pendudukan Jepang (1942-1945).
Jika kita membaca bunga rampai kesaksian berjudul Radikalisme Lokal: Oposisi dan Perlawanan Terhadap Pendudukan Jepang di Jawa (Penerbit Syarikat: 2012) yang dikumpulkan dan disunting oleh Anton Lucas, tergambar bagaimana para aktivis itu bergerak di bawah tanah, menyebarkan berkala yang dinamai “Menara Merah”. Mereka bergerak dalam gelap, berkoordinasi dengan sangat berhati-hati, dan dikendalikan oleh struktur komando yang rumit, berjenjang ala sistem sel dan tentu saja tertutup.
Dan dari beberapa kesaksian yang tercantum di buku tersebut, terdapat beberapa keterangan betapa beberapa dari mereka adalah para pemain sepakbola. Dan sebagaimana Tan Malaka di Banten, mereka pun (walau dengan sembunyi-sembunyi) masih mencoba untuk terus bermain sepakbola.
Nama-nama yang disebut di atas itulah, juga sepakbola yang dimainkan orang-orang kiri dan komunis inilah, yang dengan caranya sendiri telah membantah analisis Antonio Gramsci yang menyebut sepakbola sebagai cermin dari masyarakat yang individualistik.
Sepakbola ada di setiap penggal sejarah kemerdekaan bangsa ini. Sepakbola yang dimainkan semua orang dan di segala masa, dalam masa perang maupun damai.
Foto: Hongaria vs Inggris tahun 1953 (Getty Images)
====
*penulis adalah Chief Editor dari @panditfootball. Selain menulis tentang sepakbola, aktif juga menulis esai-esai sejarah, politik, dan budaya. Biasa beredar di dunia maya dengan akun @zenrs
(din/mfi)