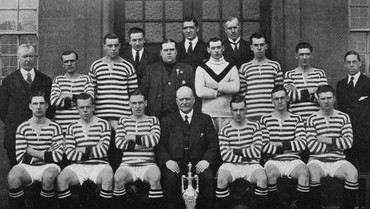Kepemilikan Pihak Ketiga (1)
Mementingkan Hak Ekonomi Ketimbang Prestasi
 Marcos Rojo (AFP/Paul Ellis)
Marcos Rojo (AFP/Paul Ellis)
Sporting Lisbon merasa rugi. Klub Portugal itu nyatanya hanya mendapat bagian 25 persen dari total nilai transfer Marcos Rojo ke Manchester United. Padahal, Benfica merasa bahwa merekalah yang paling berperan dalam mengorbitkan bakat Rojo.
Presiden Sporting, Brune de Carvalho, mencak-mencak karena dari 16 juta poundsterling mereka kebagian empat juta saja. Carvalho pun menyalahkan sistem kepemilikan ketiga atau third party ownership (TPO). Menurutnya, TPO pada akhirnya akan menjadi ancaman yang bisa merusak keuangan klub, integritas sepakbola, dan menimbulkan risiko peningkatan pengaturan skor.
Beberapa waktu ke belakang, isu kepemilikan pihak ketiga kian menghangat. Isu ini mulai menarik perhatian saat Carlos Tevez dan Javier Mascherano bergabung bersama West Ham United pada 2006. Saat itu pula klausul kontraknya mulai terbongkar. Tevez dan Mascherano diketahui dimiliki oleh investor TPO, Media Sports Investments, yang dipimpin oleh Kia Joorabchian.
Apa sebenarnya TPO?
Berawal dari Kondisi Finansial
TPO merupakan kondisi di mana ada pihak lain di luar sepakbola yang memiliki bagian atas hak ekonomi (economic rights) pesepakbola. Mereka bukan sponsor karena mendapat keuntungan dari penjualan pemain. Istilah yang lebih cocok untuk digunakan adalah investor karena sifatnya yang spekulatif.
Pada awalnya semua berawal saat kebutuhan jauh lebih tinggi dari apa yang dimiliki. Klub menginginkan pemain hebat, tapi tak cukup kuat untuk membayar uang transfer ataupun menggaji mereka. Maka, tawaran pun muncul dari pihak ketiga, yang bisa berupa agen, perusahaan manajemen olahraga, atau bahkan yang sama sekali tak terkait dengan sepakbola.
Tawaran tersebut biasanya beragam. Umumnya, pihak ketiga atau investor TPO, membayar sejumlah uang kepada klub. Sebagai gantinya, klub menyerahkan sebagian atau seluruh nilai ekonomi pemain kepada investor.
Menurut situs Law In Sport, TPO dalam industri sepakbola merupakan suatu kondisi di mana klub tidak memiliki atau tidak berhak atas seluruh kepemilikan pemain. Dampaknya, klub tidak bisa mendapatkan 100% dari nilai transfer pemain tersebut.
Konsekuensi dari kesepakatan tersebut adalah klub bisa mendapatkan dana segar dari penjualan “saham” pemain, menggaji pemain lebih murah, atau tidak menanggung biaya hidup sang pemain sama sekali. Semua tergantung pada model dan kesepakatan.
Mengenal Hak Komersial dan Hak Federatif
Investor TPO mendapatkan untung dari hak komersial pemain. Hak komersial pemain tak akan bisa didapat jika klub tak mendapatkan hak federatif (federative rights) dari operator liga.
Hak federatif merupakan hak bagi klub untuk mendaftarkan pemain berdasarkan kontrak kerja ke operator liga dan federasi. Hak federatif mencakup kebebasan yang diberikan operator liga untuk mempersilakan pemain tersebut berkompetisi dalam kompetisi resmi, serta dalam hal perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain. Hak federatif menghasilkan hak ekonomi yang biasanya berbentuk “nilai transfer”.
Ini yang membuat investor TPO tak bisa lepas dari klub. Mereka tak bisa begitu saja melakukan kesepakatan dengan pemain, lalu sesuka hati menjualnya ke klub yang meminati. Investor TPO mesti mendapat “dukungan” klub untuk mendaftarkan pemain ke operator liga. TPO mesti mencapai kesepakatan dengan klub agar bisa saling menguntungkan.
Keuntungan yang didapat tergantung dari model kerja sama yang digunakan. Apakah investor membeli “saham” pemain dari klub, atau memang telah memiliki pemain itu sepenuhnya untuk “dipinjamkan” ke klub.
Lahir Setelah Aturan Bosman
Ahli Hukum Bidang Olahraga, Ariel Reck, menuliskan bahwa konsep TPO di Amerika Selatan lahir setelah “Bosman Rule” terbentuk. “Aturan Bosman” memberikan perspektif baru bagi klub untuk tidak memiliki kekuasaan penuh atas pemain. Setelah aturan tersebut tidak ada lagi cerita klub yang mengekang pemain meski kontraknya telah habis.
Dalam Aturan Bosman, pemain dengan sisa kontrak 6 bulan diperbolehkan membuka pembicaraan dengan klub lain. Pemain yang kontraknya habis tidak memiliki nilai ekonomi lagi. Atas dasar ini, klub pemilik terdahulu tidak berhak atas sepeser pun uang transfer dari pemain ke klub baru. Aturan ini yang menimpa Arsenal, kala harus merelakan Bacary Sagna hijrah ke Manchester City dengan status “free transfer” alias gratis.
Awalnya praktik TPO di sepakbola mencengkram lebih dalam. Investor bukan hanya mencampuri hak ekonomi pemain, tapi juga hak federatif yang seharusnya hanya dimiliki oleh klub. Dengan mengambil hak federatif, pemain akan lebih tunduk pada investor TPO ketimbang pada klub.
Dalam skema seperti ini, pemain seperti dimiliki oleh “agen” meski ia dikontrak dan digaji oleh klub. Ini yang membuat FIFA menolak praktik TPO pada awal perkembangannya.
FIFA memberikan kebebasan kepada klub untuk mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan memberikan hak federatif yang menghasilkan hak ekonomi. Jika hak federatif diambil alih oleh TPO, maka klub akan semakin sulit mendapatkan pemasukan.
Penolakan FIFA ini ditolak oleh keputusan Pengadilan Abritase Internasional, CAS. CAS menerima status validitas dan legalitas kepemilikan hak ekonomi pemain saat menyidangkan kasus Espanyol dengan Atletico Velez pada 2004.
Garis besar keputusan tersebut menyatakan bahwa klub mempekerjakan pemain lewat kontrak. Dalam satu masa, hanya satu klub yang berhak mendapatkan hak federatif, artinya, pemain tersebut tidak bisa bermain di dua klub, dengan dua kontrak yang sama pada satu masa. Dengan persetujuan pemain, kontrak tersebut dapat dialihkan ke klub lain, dan sebagai gantinya, klub pemilik kontrak pemain mendapatkan sejumlah uang. Hasil dari kontrak pemain tersebut dinamakan hak ekonomi pemain. Hak ekonomi ini dapat diberikan kepada pemegang hak yang lain.
Model TPO
Saat ini diketahui ada tiga model TPO yang digunakan khususnya di Brasil. Pertama, TPO dalam bentuk pemandu bakat atau promotor. Pemandu bakat atau promotor, mempromosikan pemain muda lewat jaringan yang mereka miliki. Jika pemain tersebut diterima oleh klub, maka promotor atau pemadu bakat serta klub asal pemain muda tersebut, berhak atas hak ekonomi pemain yang biasanya berkisar 10%-20%. Syaratnya adalah pemain yang dipromosikan belum diregistrasi oleh klub lain. Pemain tersebut biasanya pemain yang tidak berstatus profesional karena belum pernah menandatangani kontrak dengan klub manapun. Kedua, klub menawarkan “saham” dalam bentuk hak ekonomi pemain. Ini bisa terjadi karena klub membutuhkan dana segar dengan cara menjual saham pemain. Biasanya, klub membutuhkan dana di muka tapi tidak ada sponsor yang bersedia. Maka, dana hasil penjualan saham pemain menjadi solusinya.
Kedua, klub menawarkan “saham” dalam bentuk hak ekonomi pemain. Ini bisa terjadi karena klub membutuhkan dana segar dengan cara menjual saham pemain. Biasanya, klub membutuhkan dana di muka tapi tidak ada sponsor yang bersedia. Maka, dana hasil penjualan saham pemain menjadi solusinya.
Model yang ketiga adalah saat investor memiliki 100% hak ekonomi pemain. Istilahnya, investor TPO meminjamkan pemain ke klub. Investor memiliki daya tawar yang besar dalam pinjam meminjam ini. Umumnya, ada klausul jika segala biaya pemain ditanggung oleh investor. Klub hanya menjadi etalase bagi pemain tersebut agar segera pindah dengan nilai besar.
Kesamaan antara dua model yang terakhir ini adalah pencantuman klausul khusus yang bisa memengaruhi keputusan klub tentang masa depan sang pemain. Klausul tersebut biasanya meminta klub untuk melepas pemain jika ada klub yang meminatinya.
Munculnya “Straw man club”
Cengkraman TPO biasanya menancap jauh lebih dalam dari apa yang kita kira. Mereka bukan tidak mungkin membeli atau menjadi pemegang saham di klub kecil. Lewat sistem seperti itu, mereka dapat dengan bebas menjual saham pemain kepada dirinya sendiri.
Saat saham pemain ada di tangan, mereka dengan sukarela mempersilakan klub lain membeli kontrak pemain dari klub yang mereka kuasai. Bagi klub-klub yang dimiliki oleh investor TPO, prestasi bukanlah tujuan akhir. Ini yang membuat klub tersebut dijuluki “straw man club” karena perannya hanyalah penggembira, dan sebagai pemasok pemain.
Jika pemain yang mereka miliki ditawar jauh di bawah harga yang diinginkan, maka pemain tersebut bisa dipinjamkan terlebih dahulu dengan nilai yang besar. Ini terjadi saat klub peminat masih kurang yakin dengan penampilan sang pemain. Kerja sama ini biasanya disertai opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Kehadiran “straw man club” ini membuat liga tak lagi kompetitif, karena prestasi hanyalah bonus alternatif.
**
Investor TPO pada dasarnya menjalin hubungan saling menguntungkan dengan klub. Mereka membantu keuangan klub. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan hak ekonomi pemain.
Aturan Bosman membuat daya tawar klub terhadap pemain lebih rendah. Pemain mesti dikontrak dalam jangka waktu panjang untuk menghindari agar ia tak pindah dengan gratis.
Untuk pemain muda, kontrak jangka panjang biasanya dilakukan untuk jaga-jaga siapa tahu suatu saat ia bersinar. Namun, klub tentu tak mau berspekulasi dengan masa depan si pemain. Kontrak jangka panjang sama saja memperpanjang beban finansial klub yang harus menggaji pemain tersebut. Maka, penjualan saham pemain menjadi hal yang paling realistis. Mereka bisa menjual separuh hak ekonomi pemain, guna mendapatkan dana segar di muka.
Jika si pemain tujuan diminati dengan harga tinggi, klub untung, investor pun untung. Namun, jika karir si pemain dibeli dengan harga yang di bawah harapan, setidaknya klub sudah mendapat uang dari investor.
Umumnya terdapat tiga model kerjasama TPO yang biasa ditemukan di Amerika Selatan. Model-model tersebut dipertajam lagi lewat klausul yang tertera pada kontrak pemain. Investor bisa saja “memaksa” klub untuk menjual pemain jika ada klub yang meminatinya, dengan konsekuensi, investor menanggung semua biaya hidup sang pemain di klub.
Lalu, apa yang membuat TPO menjadi tren bagi mayoritas kesebelasan di Amerika Selatan? Mengapa UEFA dengan tegas menolak kehadiran TPO?
[Bersambung]
===
* Akun twitter penulis: @Aditz92 dari @panditfootball