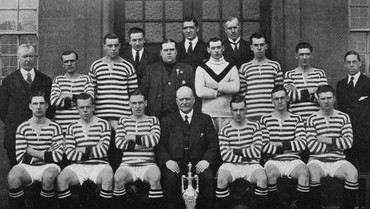Manajemen Olahraga (Bagian 1)
Peran Penting Kebijakan Pemerintah dalam Memajukan Olahraga Sebuah Negara
 Julian Finney/Getty Images
Julian Finney/Getty Images
Dari sekitar 250 juta penduduk di Indonesia, apakah sebegitu sulitnya mencari sebelas pemain sepakbola terbaik untuk bermain bersama di satu lapangan hijau? Pertanyaan di atas seolah sudah "basi" dan agak membosankan untuk didengar.
Tapi sejujurnya, pertanyaan itu memang belum memiliki jawaban yang sahih. Kalau boleh jujur, masalah di atas bukan hanya terjadi pada sepakbola, tetapi juga di banyak cabang olahraga populer seperti bola basket, bola voli, atletik, dan bahkan bulutangkis.
Untuk olahraga secara umum, seandainya kita bandingkan Indonesia dengan negara seperti Jepang (126 juta penduduk), Jerman (81 juta), Kanada (35 juta), Australia (23 juta), Belanda (17 juta), Kazakhstan (17 juta), Hongaria (9 juta), dan bahkan Thailand (67 juta), kita sudah sangat jauh tertinggal.
Hal di atas bisa kita lihat langsung cerminannya dari hasil peralihan medali di Olimpiade 2012 di London, Inggris Raya. Negara-negara tadi berada di atas Indonesia yang menduduki peringkat 63, dengan hanya satu medali perak dan satu medali perunggu.
Thailand sedikit berada di atas Indonesia (2 perak dan 1 perunggu), sementara Kanada (1-5-12), Belanda (6-6-8), Kazakhstan 7-1-5), Jepang (7-14-17 perunggu), Australia (7-16-12), Hongaria (8-4-6); dan Jerman (11-19-14) sepertinya masih terlalu perkasa jika dibandingkan dengan negara kita.
Hal ini juga berlaku di sepakbola, setidaknya jika dilihat dari peringkat FIFA. Pertanyaan mengenai prestasi negara kita di pentas dunia semakin bertambah besar dengan jawaban yang juga tak kunjung muncul.
Bagi yang skeptis sekalipun, ada wajarnya juga mereka yang mempertanyakan peran olahraga di mata dunia internasional. Sebegitu pentingnyakah olahraga? Sebegitu pentingnyakah sepakbola?
Olahraga tentu sangat penting, begitu juga dengan sepakbola. Dengan olahraga, sebuah negara bisa mendapatkan pengakuan internasional. Tidak ada yang meragukan kualitas Jerman dan Brasil, misalnya, dalam cabang olahraga sepakbola. Begitu pula h yang identik dengan bulutangkis, tenis meja, dan senam. Atau Selandia Baru dan Australia di rugbi, Jamaika di atletik, Amerika Serikat di bola basket, Inggris di bersepeda dan berkuda, serta masih banyak contoh lainnya.
Pengakuan dunia ini bisa dinilai dengan mudah melalui prestasi. Sedangkan banyak cara untuk menilai prestasi, salah satunya dengan perolehan medali di Olimpiade, atau juga juara Piala Dunia, menjadi tuan rumah acara olahraga besar, serta level "prestasi" yang paling bawah yaitu angka partisipasi yang aktif.
Masalah pada Manajemen Olahraga
Ironi dari jumlah penduduk Indonesia yang menempati peringkat empat dunia di bawah China (1,37 miliar penduduk), India (1,27 miliar), dan Amerika Serikat (321 juta), tidak dapat dihindari lagi. Masalah perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah atlet berprestasi pastinya merupakan angka yang saling berkolerasi: Semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi pula kemungkinan mencetak atlet berprestasi. Begitu, bukan?
Pada kenyataannya tidak semudah itu. Ada banyak hal yang berpengaruh selain jumlah penduduk, antara lain adalah pembinaan, kebiasaan, jumlah fasilitas, faktor genetik (alam), sampai kepada yang akan kita bahas kali ini: kebijakan pemerintah (sport governance).
Faktor-faktor di atas memang sangat beragam. Namun, dari berbagai masalah, pasti ada langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya.
Sekitar awal September kemarin, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai manajemen olahraga di Jepang selama beberapa pekan. Acara tersebut bernama NIFISA (National Institut of Fitness and Sports – International Sport Academy) yang berbentuk seminar sebagai bagian dari persiapan Jepang dalam melaksanakan Olimpiade 2020 di Tokyo, ibu kota Jepang.
Seperti yang kita tahu, Jepang adalah negara yang sudah berada jauh di depan Indonesia dalam urusan olahraga, termasuk sepakbola.
Banyak hal yang membuat saya kagum dengan situasi olahraga di Jepang, salah satunya adalah mengenai kebijakan pemerintah yang mereka canangkan melalui kampanye sebelumnya "Sports for All," yang dilanjutkan dengan kampanye berikutnya, yaitu "Sport for Tomorrow", yang semakin gencar dilakukan menjelang Olimpiade 2020.
Untuk kampanye "Sports for All", kita bisa melihat kembali tulisan Abimanyu Bimantoro (Lihatlah Jepang, Kita Masih Jauh dari Piala Dunia) yang juga sempat belajar ke Jepang pada akhir tahun 2014.
Sedangkan dalam seminar manajemen olahraga yang saya ikuti bulan lalu di Kanoya dan Osaka, pembahasan mengenai kebijakan pemerintah di bidang olahraga (sport policy) membahas banyak contoh kasus antara lain selain dari Jepang, juga dari Belanda, Kanada, dan Jerman, dengan masing-masing pembicara berasal dari negara-negara tersebut.
Antara Tradisi dan Ambisi
Ada tiga hal utama jika kita mengaitkan olahraga dengan kebijakan sebuah negara, yaitu bisnis, masyarakat, dan negara itu sendiri. Tiga hal tersebut biasa menimbulkan pertentangan di antara tradisi dan ambisi, sehingga kebijakan olahraga (sport governance) berperan dalam menyeimbangkan bisnis, masyarakat, dan negara.
Yang dimaksud tradisi di sini adalah ideologi, identitas, dan kebiasaan. Sedangkan ambisi lebih kepada sesuatu yang ingin diraih, biasanya berupa medali emas, menjadi tuan rumah sebuah acara olahraga besar seperti Olimpiade atau Piala Dunia, dan memperoleh kesuksesan materi.
Dr. Inge Claringbould, seorang associate professor di Universiteit Utrecht di Belanda, menjadi salah satu pembicara pada seminar yang saya ikuti. Ia menyatakan bahwa di Eropa, organisasi olahraga adalah organisasi yang bisa menyedot banyak domain masyarakat.
Namun, mereka juga menghadapi masalah yang umum terjadi, yaitu partisipan yang masih terlalu jomplang terutama pada masalah jenis kelamin, umur, etnis, pendidikan, dan pendapatan.
Misalnya saja, masih lebih banyak laki-laki yang berpartisipasi pada olahraga daripada perempuan, begitu juga kadang terdapat diskriminasi umur, etnis, dan kondisi fisik (disabilitas) dan sebagainya.
Pada prinsipnya, terdapat beberapa konsep yang harus disadari oleh para pelaku olahraga di sebuah negara yang dibagi kepada pemerintah, olahraga itu sendiri, dan juga pengorganisasiannya.
Pemerintah, misalnya, harus mampu memiliki sikap untuk mengendalikan, tidak peduli isu publik. Mereka adalah kontrol inti atau jaringan organisasi yang harus bisa menghubungkan banyak aspek di masyarakat.
Kemudian kita juga jangan sampai melupakan konsep utama olahraga, yaitu untuk bermain. Seperti kata dasar "sport" yang berasal dari "dis-ports" dari Bahasa Prancis Kuno yang berarti "untuk menghibur diri" atau "untuk menyenangkan diri". Selain itu, olahraga juga harus memiliki konsep yang mengutamakan kepentingan umum, memiliki nilai-nilai logika dan aturan masing-masing.
Sementara organisasi lebih kepada konteks sosial yang logis dan jitu, terstruktur, serta menjadi alat/instrumen bagi masyarakat untuk mencapai tujuan, dalam hal ini adalah untuk sehat, untuk bermain (mendapatkan kesenangan), dan pada akhirnya memperoleh prestasi.
Pentingnya Organisasi Olahraga
Dr. Claringbould selanjutnya memberikan contoh kasus dari Belanda untuk memahami pentingnya kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan olahraga. Dari 17 juta penduduk di Belanda, mereka memiliki 3,9 juta atlet dan 28.780 klub atau organisasi olahraga. Sementara untuk para pekerja di bidang olahraga, sebanyak 1,5 juta mereka peroleh dari sukarelawan (volunteer).
Institusi olahraga di Belanda juga berlapis-lapis mulai dari klub olahraga, pemerintah lokal, akademi olahraga, asosiasi olahraga nasional, federasi olahraga nasional, komite olimpiade nasional, pusat olahraga regional, kementrian olahraga, sampai lottery dan berbagai macam sponsor.
[Bagan orientasi olahraga jika dikaitkan dengan kebijakan negara]
Dari bagan di atas, ia memberikan contoh bahwa ketiga aspek di atas berupa gairah (passion), keuntungan (profit), dan kepentingan umum (public), saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
Gairah yang diikuti oleh niat untuk mendapatkan keuntungan akan melahirkan komersialisasi, sementara gairah yang diikuti oleh kemauan untuk mementingkan kepentingan umum sebaliknya bisa menciptakan rasa nasionalisme.
Penggabungan atau kombinasi antara keuntungan dan kepentingan umum bisa dicapai dengan profesionalisme. Namun, di sini timbul pertanyaan, apakah ekspektasi (dan pengaruh) dari negara dan bisnis justru menjauhkan konsep dan prinsip olahraga? Kemudian juga bagaimana cara menyeimbangkan gairah dengan profesionalisme untuk mencapai ekspektasi tersebut?
Hal ini tentunya akan terfokus kepada bagaimana strategi pemerintah dalam menyikapinya. Secara ideal, pemerintah harus memahami masyarakat, memiliki perspektif yang multi-layered dan multi-actor, dan memiliki prinsip yang efisien.
Multi-layered dan multi-actor di sini berasal dari lapisan-lapisan pihak yang terlibat dalam olahraga (klub olahraga, pemerintah lokal, akademi olahraga, asosiasi olahraga nasional, dst) sehingga pemerintah bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, dalam kementerian olahraga, harus ada anggota aktif dari masyarakat berjenis kelamin perempuan, seluruh etnis, kelompok umur yang beragam, dan lain-lain.
Kenapa Sebuah Negara Membutuhkan Kebijakan Olahraga (Sport Policy)?
Nelson Mandela pernah mengungkapkan konsep "Power of sport" di mana olahraga memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, menginspirasi, mempersatukan manusia, "berbicara" kepada generasi muda dengan bahasa yang mudah dipahami, dan menciptakan harapan.
John Ross Cooper, seorang assistant professor dari Kanada, pembicara lainnya di acara seminar yang saya ikuti, memberikan contoh kasus yang juga berasal dari negara kelahirannya, Kanada. Menurutnya, perbedaan masyarakat di Kanada (kulit putih, Asia, Aborigin, kulit hitam, Amerika Latin, dll) dipersatukan oleh olahraga, terutama melalui perhelatan Olimpiade. Bahkan dalam Olympic torch relay yang melibatkan lebih banyak masyarakat.
Dalam aplikasinya, tingkatan olahraga di Kanada berasal dari komunitas (klub, pemerintah lokal, sekolah, universitas), provinsi, nasional, dan internasional. Untuk itu juga mereka terus memaksimalkan orang yang paling berpengaruh, seperti atlet, pebisnis, dan juga opini publik dan media.
Setelah mengadakan promosi olahraga dengan tajuk "Own the Podium", olahraga di Kanada pada akhirnya bisa mengubah masyarakat. Kebijakan olahraga di Kanada ini antara lain memiliki 5 tahapan untuk mencapai jalur kesuksesan.
1. Perkenalan kepada olahraga (introduction): mempelajari kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap yang benar dalam berolahraga.
2. Olahraga hiburan (recreational): kesempatan untuk berpartisipasi sebanyak-banyaknya dalam olahraga, mengedepankan hiburan, kesehatan, interaksi sosial, dan relaksasi.
3. Olahraga kompetitif (competitive): kesempatan untuk berkembang secara sistematis dan mengukur performa dengan partisipan lainnya di dalam kompetisi yang aman dan nyaman.
4. Olahraga tingkat tinggi (high performance): secara sistematis memperoleh hasil kelas dunia pada level tertinggi di kompetisi internasional dengan adil dan mengedepankan prinsip fair play.
5. Pengembangan olahraga (development): olahraga digunakan sebagai alat untuk perkembangan sosial dan ekonomi, dan mempromosikan nilai-nilai positif di dalam dan di luar negeri.
Hal ini memang tidak terjadi secara instan, butuh waktu bertahun-tahun, sama seperti Jepang juga (kampanye "Sports for All" dan "Sports for Tomorrow"). Tapi secara umum, beberapa strategi efektif yang mereka lakukan adalah dengan memperbolehkan anak-anak (tak terkecuali, misalnya laki-laki dan perempuan, ada yang cacat, dan dari berbagai macam etnis) untuk berpartisipasi di olahraga sejak dini, bahkan bisa jadi kewajiban di tingkat sekolah melalui pendidikan jasmani (physical education).
Ini mungkin yang Indonesia kurang kuat untuk miliki. Saat ini saja misalnya, ada berapa sekolah dasar (SD) sampai tingkat selanjutnya (SMP dan SMA) yang mewajibkan Penjaskes ke dalam mata pelajaran. Berapa kali anak-anak sekolah kita berolahraga setiap pekannya, apakah anak-anak Indonesia memerlukan ekstra kurikuler tambahan untuk berolahraga
Bagaimana masyarakat Indonesia bisa sehat, senang (dari bermain di olahraga), dan berprestasi, jika pendidikan olahraga diperlakukan seperti "anak tiri" di sekolah kita? Opini miring seperti, "Apa sih, pentingnya olahraga? Lebih penting juga belajar," harus dihindari untuk menciptakan keseimbangan bagi negara dalam kaitannya dengan olahraga.
Padahal menurut penelitian di bidang sains olahraga, pada kenyataannya olahraga bisa meningkatkan kemampuan seorang anak untuk belajar, yaitu dengan menstimulasi otak mereka. Melalui langkah-langkah panjang ini lah peran penting pemerintah diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal.
====
* Penulis biasa menulis soal sport science untuk situs @panditfootball, beredar di dunia maya dengan akun @dexglenniza